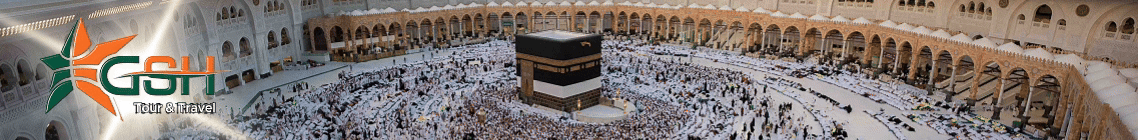Harian Masyarakat | Ledakan di SMA 72 Jakarta, Jumat pekan lalu, mengguncang publik. Sebanyak 96 orang terluka, tiga di antaranya luka berat. Polisi menyebut pelaku adalah siswa sekolah itu sendiri, yang ditemukan terkapar bersimbah darah di lokasi kejadian. Di samping tubuhnya, ditemukan senjata mainan bertuliskan nama-nama pelaku teror dunia.
Penyelidikan polisi menyebut pelaku tidak terafiliasi jaringan teror mana pun. Ia disebut sebagai “anak berhadapan dengan hukum” karena masih di bawah umur. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, pelaku bertindak karena dorongan emosional dan rasa keterasingan. “Ia merasa sendiri dan tidak punya tempat untuk menyampaikan keluh kesah, baik di rumah maupun di sekolah,” ujarnya pada 11 November 2025.
Densus 88 juga mengungkap pelaku bergabung dalam komunitas online pengagum kekerasan. Grup itu berisi unggahan aksi brutal yang saling diapresiasi sebagai “tindakan heroik.” Pelaku disebut terinspirasi enam penyerangan di luar negeri, termasuk tragedi penembakan Columbine (Amerika Serikat, 1999) hingga serangan di Masjid Christchurch (Selandia Baru, 2019).
Prabowo Rencanakan Pembatasan Game Online
Presiden Prabowo Subianto merespons peristiwa itu dengan rencana membatasi akses pelajar terhadap gim online bergenre kekerasan seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG). Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kebijakan ini muncul karena gim perang dinilai membuat anak mudah mengenal senjata dan menganggap kekerasan hal biasa.
“Di situ ada jenis-jenis senjata. Mudah sekali dipelajari, lebih berbahaya lagi,” kata Prasetyo di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, 9 November 2025. Ia menilai pengaruh gim online bisa membentuk pola pikir generasi muda yang permisif terhadap kekerasan.
Namun, hingga kini pemerintah belum memaparkan langkah teknis. Kementerian Komunikasi dan Digital juga belum memberikan tanggapan terkait mekanisme pembatasan itu.
Kritik: Kebijakan Reaktif yang Tak Menyentuh Akar Masalah
Sejumlah pakar menilai kebijakan pelarangan gim kekerasan terlalu sempit dan reaktif. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudin menilai, kekerasan di sekolah tidak bisa dikerucutkan hanya pada faktor permainan. “Salah sasaran kalau penyebab insiden ini dikerucutkan ke kekerasan dalam game,” ujarnya. Ia menekankan bahwa paparan kekerasan anak jauh lebih luas, termasuk dari media sosial.
Sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, menyebut kebijakan ini sudah terlambat. “Kekerasan digital sudah lama dikonsumsi anak Indonesia, dari gim, televisi, hingga konten media sosial. Mereka tidak lagi sensitif terhadap kekerasan,” ujarnya.
Menurut Ida, solusi yang efektif justru dengan kebijakan komprehensif: membatasi produksi dan akses terhadap seluruh bentuk produk kekerasan di media digital.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga menilai pembatasan gim tidak cukup. Koordinator P2G, Iman Zaenatul Heri, menegaskan perlunya kedaulatan data pendidikan agar pemerintah dapat melindungi siswa dari konten berbahaya. “Komdigi ini kan tidak pernah berhasil menghentikan judi online. Bagaimana mungkin kami percaya bisa menghentikan konten kekerasan dalam gim?” kata Iman.
Analisis Psikolog dan Pakar Anak: Kekerasan Berakar dari Rasa Terasing
Psikolog anak Rose Mini Agoes Salim menilai larangan gim kekerasan tak akan menghentikan tindak kekerasan. “Kalau ini dianggap bentuk hukuman, maka biasanya tidak bertahan lama. Anak akan mencari jalan lain,” ujarnya.
Rose menjelaskan, perilaku kekerasan sering kali muncul dari siklus luka batin. Anak yang pernah menjadi korban perundungan atau tekanan akademik bisa berbalik menjadi pelaku. “Kalau luka itu disimpan, lama-lama jadi racun. Kalau tidak menyakiti diri sendiri, ia bisa menyakiti orang lain,” katanya.
Retno Listyarti, pemerhati pendidikan, menilai gim kekerasan memang punya pengaruh, tapi bukan faktor utama. Ia menilai sistem pengasuhan dan pendidikan yang belum sehat jauh lebih berperan. “Tanpa pembenahan pola pengasuhan di sekolah dan keluarga, pembatasan gim tidak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Retno menyoroti pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang belum berjalan efektif. Beleid itu mengatur teknis penanganan kekerasan, sanksi, pemulihan korban, dan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). “Sayangnya banyak sekolah belum punya TPPK atau tidak berfungsi optimal,” katanya.
Jejak Kasus Kekerasan di Sekolah
Kasus di SMA 72 bukan yang pertama kali kekerasan ekstrem muncul di lingkungan sekolah. Pada 2023, seorang siswa SMP di Temanggung membakar sekolah karena dendam setelah dirundung. Kasus serupa terjadi di Bekasi pada 2006 dan di Aceh Besar pada November 2025, ketika seorang santri membakar asrama akibat perundungan.
Pakar kriminologi anak, Haniva Hasna, menilai konsumsi kekerasan digital sehari-hari dapat menumpulkan empati. “Setiap hari melihat darah dan kekerasan membuat seseorang menormalisasi hal itu,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya penyelidikan mendalam terhadap motif pelaku SMA 72. “Apakah benar dia korban bullying? Ini bukan keributan antargeng, pasti ada sebab yang lebih dalam,” katanya.
Haniva juga mengingatkan bahwa fenomena serangan di sekolah sudah lama menjadi ancaman di negara lain. Data K-12 School Shooting Database mencatat 330 penembakan di sekolah-sekolah Amerika Serikat dalam satu tahun terakhir. Pola penyebabnya mirip: isolasi sosial, perundungan, trauma, dan ketertarikan terhadap senjata serta kekerasan.
Tantangan Kebijakan: Pencegahan, Bukan Sekadar Pelarangan
Rencana pembatasan gim online dinilai tidak akan efektif tanpa perubahan sistemik di pendidikan dan keluarga. Rose Mini menegaskan, perubahan perilaku anak hanya bisa bertahan jika disertai pemahaman internal. “Yang berkelanjutan itu kalau anak paham kenapa ia tidak boleh melakukannya,” katanya.
Para pakar sepakat, negara harus fokus pada pencegahan kekerasan, bukan sekadar menutup akses terhadap gim. Upaya itu mencakup:
- Penanganan serius terhadap kasus perundungan di sekolah.
- Penguatan peran guru, konselor, dan TPPK dalam membina siswa.
- Literasi digital agar anak paham risiko konten kekerasan.
- Kebijakan data pendidikan yang melindungi dan memantau perilaku daring siswa.
Saatnya Fokus ke Akar Masalah
Ledakan di SMA 72 Jakarta menyingkap masalah lebih besar: lemahnya sistem perlindungan anak dari kekerasan digital, sosial, dan emosional. Pembatasan gim online mungkin bisa mengurangi paparan visual kekerasan, tapi tanpa penanganan akar masalah, perundungan, isolasi sosial, dan kegagalan sistem pendidikan, kekerasan serupa bisa terulang.
Seperti disampaikan sosiolog Ida Ruwaida, “Kita tidak cukup hanya membatasi akses. Negara harus berani mengatur ulang ekosistem kekerasan di dunia digital.”